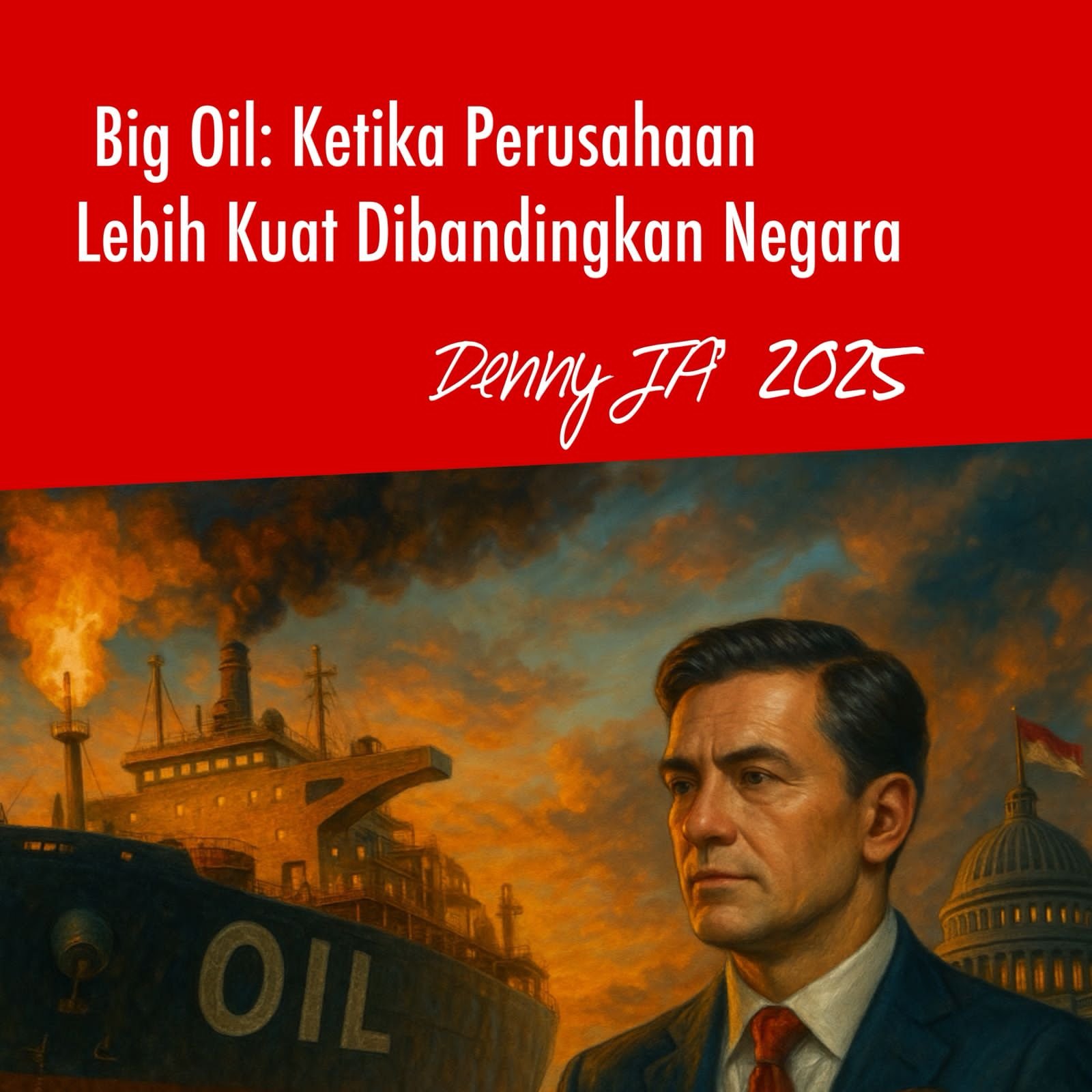Oleh: Denny JA
“Mereka tak membawa bendera. Tapi di balik layar, mereka menentukan siapa yang mengangkat senjata dan siapa yang menjual solar,”
Pada musim semi 2004, seorang mantan analis CIA yang bekerja lepas untuk perusahaan minyak menceritakan pengalaman yang tak pernah ia lupakan.
Ia sedang menghadiri rapat tertutup di kantor pusat ExxonMobil di Irving, Texas.
Di lantai 22, ia dibawa masuk ke sebuah ruangan tanpa jendela, sunyi, dan sejuk, yang dindingnya hanya dihiasi satu hal: sebuah peta dunia raksasa.
Tapi bukan peta geopolitik. Tak ada garis negara, tak ada nama ibu kota. Yang terpampang adalah sebaran cadangan minyak dan gas bumi: sumur yang aktif, wilayah potensial, rute pipa, ladang yang sedang disengketakan.
Setiap titiknya bukan menandai penduduk, melainkan volume cadangan. “Di sini,” kata salah satu eksekutif, menunjuk wilayah padang pasir tanpa nama, “ada lebih banyak nilai daripada seluruh GDP Ghana.”
Di luar, dunia bicara soal perang Irak, soal senjata pemusnah massal yang tak pernah ditemukan. Tapi di dalam ruangan itu, senjata sesungguhnya adalah data cadangan minyak.
Ia tak terlihat, tak menggelegar, tapi menggerakkan segalanya. Presiden mungkin tahu lokasi musuh. Tapi CEO kami tahu lokasi minyak.
-000-
Apa yang bisa Indonesia pelajari dari adegan tersebut?
Apa makna dari kekuasaan di era modern ketika peta-peta kekuasaan tidak lagi dibuat oleh negara, tapi oleh korporasi?.
Sejarah mencatat bahwa negara selalu menjadi aktor utama dalam membentuk peradaban: penaklukan, hukum, pendidikan, pertahanan.
Namun sejak John D. Rockefeller membangun Standard Oil pada abad ke-19, terjadi pergeseran sunyi dalam arsitektur kekuasaan dunia.
Standard Oil tak hanya menguasai 90% distribusi minyak AS, tapi juga menulis ulang aturan permainan kapitalisme.
Ketika Standard Oil dipaksa bubar tahun 1911, dunia tidak menyaksikan kematian kekuasaan, melainkan kelahiran baru dari rahim yang sama.
Muncul “Seven Sisters”—tujuh perusahaan minyak raksasa yang mencengkeram ladang-ladang energi dari Teluk Persia hingga Teluk Meksiko.
Iran, 1953. Pemerintah demokratis yang terpilih secara sah—Mohammad Mossadegh—berani menasionalisasi minyak Iran dari tangan Anglo-Iranian Oil Company (cikal bakal BP).
Hasilnya? Ia digulingkan lewat kudeta rahasia yang didukung oleh CIA dan MI6. Minyak kembali ke tangan perusahaan.
Nigeria, 1990-an. Aktivis lingkungan Ken Saro-Wiwa digantung oleh pemerintah militer. Dosa utamanya: menuntut keadilan atas pencemaran Shell di Delta Niger.
Perusahaan tak hanya dilindungi oleh hukum kolonial, tapi juga oleh keheningan internasional.
Irak, 2003. Perang yang digagas atas nama demokrasi, ternyata membuka jalan bagi konsesi migas internasional yang sebelumnya tertutup selama era Saddam Hussein.
Seorang jenderal AS pernah berbisik: “Kami membuka jalan bagi Chevron dan Halliburton. Itu saja cukup.”
-000-
Big Oil hari ini tak hanya menjual bensin. Mereka mengendalikan rantai nilai dari bawah tanah hingga ke nosel SPBU.
Mereka memiliki kapal tanker sendiri, pelabuhan LNG sendiri, sistem arbitrase global sendiri.
Ketika BP bergabung dengan Amoco, Exxon dengan Mobil, Chevron dengan Texaco, itu bukan sekadar merger bisnis. Itu adalah penggabungan kerajaan.
Dalam narasi pasar bebas, semua pelaku seolah punya kesempatan yang sama. Tapi jika satu pihak mengendalikan infrastruktur dasar—pipa, pelumas, logistik, regulasi—lalu di mana letak kompetisi?
Pada 1977, ilmuwan ExxonMobil telah mengetahui dengan cukup akurat bahwa emisi karbon dari bahan bakar fosil akan menyebabkan pemanasan global signifikan.
Tapi alih-alih bertindak, mereka justru mendanai think tank yang menyebarkan keraguan akan sains iklim.
Mereka tahu bumi akan terbakar, tapi yang penting adalah menjaga agar saham tetap hijau.
BP mengganti logo menjadi bunga. Shell membuat iklan anak-anak menggambar masa depan cerah. Tapi 95% portofolio mereka tetap berada di minyak dan gas.
Greenwashing menjadi strategi komunikasi yang paling mahal sekaligus paling nihil makna. Daun hijau bukan simbol hidup, tapi tirai untuk menyembunyikan bau asap.
-000-
Chevron menggugat Ekuador setelah pengadilan negara itu memerintahkan ganti rugi atas pencemaran Amazon.
Bukannya membayar, Chevron membawa kasus ke arbitrase internasional—dan menang. Shell dituntut oleh pengungsi Ogoni, tapi selalu berlindung di balik jaringan hukum lintas yurisdiksi.
Ketika warga biasa tunduk pada hukum nasional, perusahaan besar tunduk pada para akuntan dan pengacara internasional.
Jika kekuasaan berada pada tangan perusahaan, lalu bagaimana rakyat bisa melawan?
Di belahan dunia lain, anak-anak muda menggugat negaranya karena tak melindungi masa depan iklim. Fridays for Future mengguncang jalanan Eropa.
Komunitas adat di Kanada dan Amazon mendirikan benteng-benteng damai. Film dokumenter seperti There Will Be Blood atau Dark Waters membongkar wajah kelam di balik logo yang bersinar.
Akar rumput memang tak setinggi menara minyak. Tapi jika mereka tumbuh serentak, beton pun bisa retak.
-000-
Apa yang bisa Indonesia Pelajari?
Indonesia adalah negara kaya sumber daya, namun terlalu lama hidup dalam ilusi bahwa negara selalu lebih berdaulat dari perusahaan.
Pertanyaannya kini: jika ExxonMobil bisa menembus istana, Shell bisa menekan negara lewat arbitrase, dan BP bisa menulis ulang narasi iklim, maka seberapa kuat lembaga-lembaga kita menahan dominasi itu?
Apakah kita menyiapkan generasi pembuat kebijakan yang paham hukum energi global? Apakah kita hanya akan jadi pasar—atau menjadi arsitek masa depan energi kita sendiri?
Negara didefinisikan oleh rakyat dan wilayah. Perusahaan didefinisikan oleh aset dan laba.
Tapi dalam dunia modern, siapa yang benar-benar punya kuasa? Siapa yang menentukan arah teknologi, perang, dan cuaca?
Mungkin masa depan tidak hanya menuntut demokrasi politik. Tapi juga demokrasi energi.
Karena ketika sumur minyak lebih kuat dari parlemen, dan CEO lebih didengar daripada presiden, maka pertanyaannya bukan hanya soal minyak.
Tapi soal siapa yang berhak bermimpi dan siapa yang hanya boleh menonton.
-000-
Di abad mendatang, yang mati bukan hanya minyak. Tapi mitos bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab bisa bertahan selamanya.
Dan dari reruntuhan itu, kita akan belajar: bahwa bukan kekuatan yang membuat kita layak memimpin dunia. Tapi keberanian untuk bertanggung jawab.***
Jakarta, 6 Juli 2025
REFERENSI
• Steve Coll, Private Empire: ExxonMobil and American Power (2012)
• Naomi Oreskes & Erik Conway, Merchants of Doubt
• Film dokumenter: ExxonMobil: The Climate Deception, The Power of Big Oil (PBS Frontline)
-000-
Ratusan esai Denny JA soal filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, politik demokrasi, sejarah, bisnis dan marketing, positive psychology, catatan perjalanan, review buku, film dan lagu, bisa dilihat di FaceBook Denny JA’s World
https://www.facebook.com/share/16UPvauPqs/?mibextid=wwXIfr